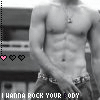Bekerja di sebuah rumah sakit tempat merawat pasien yang baru mengalami stroke merupakan sebuah pilihan yang tidak boleh ragu-ragu. Mereka biasanya sangat ingin hidup atau justru ingin segera mati. Ini tampak dari sorot mata mereka. Albert mengajariku banyak hal tentang stroke.
Bekerja di sebuah rumah sakit tempat merawat pasien yang baru mengalami stroke merupakan sebuah pilihan yang tidak boleh ragu-ragu. Mereka biasanya sangat ingin hidup atau justru ingin segera mati. Ini tampak dari sorot mata mereka. Albert mengajariku banyak hal tentang stroke.  Pada suatu petang ketika aku sedang berkeliling melakukan pemeriksaan, aku bertemu dengannya, meringkuk dalam posisi seperti janin dalam kandungan. Ia seorang pria tua berwajah pucat pasi dengan tampang seperti orang mati, kepalanya hampir tidak kelihatan di balik selimutnya. Ia tidak bereaksi ketika aku memperkenalkan diri, dan ia tidak menyahut sepatah kata pun ketika aku mengatakan bahwa ia harus “segera” makan malam.
Pada suatu petang ketika aku sedang berkeliling melakukan pemeriksaan, aku bertemu dengannya, meringkuk dalam posisi seperti janin dalam kandungan. Ia seorang pria tua berwajah pucat pasi dengan tampang seperti orang mati, kepalanya hampir tidak kelihatan di balik selimutnya. Ia tidak bereaksi ketika aku memperkenalkan diri, dan ia tidak menyahut sepatah kata pun ketika aku mengatakan bahwa ia harus “segera” makan malam.Di ruang jaga perawat, seorang perawat junior memberiku sedikit informasi tentang dirinya. Ia tidak memiliki siapa pun. Ia merasa telah hidup terlalu lama. Istrinya telah tiga puluh tahun meninggal, kelima anakaya entah berada dimana.
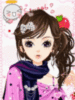 Baiklah, mungkin aku dapat menolongnya. Sebagai seorang janda yang meskipun bertubuh subur namun cukup cantik dan jarang bergaul dengan kaum pria di luar pekerjaan, kupikir aku dapat memuaskan salah satu kebutuhanku. Anggap saja ini sebuah petualangan.
Baiklah, mungkin aku dapat menolongnya. Sebagai seorang janda yang meskipun bertubuh subur namun cukup cantik dan jarang bergaul dengan kaum pria di luar pekerjaan, kupikir aku dapat memuaskan salah satu kebutuhanku. Anggap saja ini sebuah petualangan.Keesokan harinya aku mengenakan pakaian ynag bukan seragam seperti biasanya, tetapi tetap berwarna putih. Lampu tidak kunyalakan. Tirai kututup rapat.
Albert langsung membentak, menyuruhku keluar. Aku justru menarik sebuah kursi ke dekat pembaringannya, kemudian duduk dengan kaki menyilang dan dagu agak tengadah. Aku memberinya senyum yang sesempurna mungkin.
“Apa tidak salah? Di luar sudah banyak wanita menunggu.”
Ia tampak agak tersinggung. Tetapi aku berbicara panjang lebar tentang betapa aku senang bekerja di unit rehabilitasi karena aku dapat mendorong orang mencapai potensi maksimum mereka. Ini tempat yang penuh dengan kemungkinan. Ia tidak menyahut sepatah kata pun.
Dua hari kemudian ketika aku mendapatkan giliran jaga, aku diberitahu bahwa Albert telah menanyakan kapan aku bertugas di situ lagi. Kawan-kawan di situ menyebut pria itu “pacarku” dan gosip ini segera beredar. Aku tidak pernah membantah. Bahkan di luar kamarnya, aku berseru kepada yang lain untuk tidak mengganggu “Albert-ku.”
 Dua bulan kemudian, Albert sudah menggunakan alat bantu berjalan. Dan pada bulan ketiga, ia meningkat ke penggunaan sebatang tongkat penyangga. Pada hari ketika ia diperbolehkan pulang, kami merayakannya dengan sebuah pesta. Albert dan aku berdansa dengan iringan lagu Edith Piaf. Ia bukan pria romantis, tetapi dalam berdansa ia mampu memegang kendali. Aku tak dapat menahan air mataku saat kami harus berpisah.
Dua bulan kemudian, Albert sudah menggunakan alat bantu berjalan. Dan pada bulan ketiga, ia meningkat ke penggunaan sebatang tongkat penyangga. Pada hari ketika ia diperbolehkan pulang, kami merayakannya dengan sebuah pesta. Albert dan aku berdansa dengan iringan lagu Edith Piaf. Ia bukan pria romantis, tetapi dalam berdansa ia mampu memegang kendali. Aku tak dapat menahan air mataku saat kami harus berpisah.Secara berkala aku menerima kiriman bunga mawar, bunga krisan, dan kacang yang gurih. Ia telah berkebun lagi.
Atasanku memanggil, waktu aku sedang memandikan seorang pasien. “Oh, jadi Anda! Wanita yang mengingatkan Albert-ku bahwa ia seorang pria sejati!” kepalanya tengadah, senyumnya mengembang ketika ia memberiku sebuah undangan untuk datang ke pesta perkawanan mereka.
Magi Hart